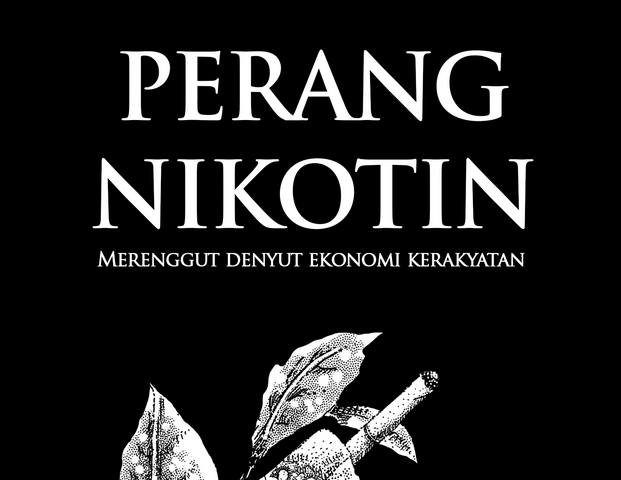Saya mengenal rokok mungkin sudah lama. Kakek saya adalah perokok kretek kuat. Amat sangat jarang ia membeli rokok filter. Ia menyukai rokok kretek dan sering kali menghisap “anau”: Tembakau yang dilinting dengan daun anau.
Mulanya saya tidak suka dengan kretek. Sebabnya, aib bagi pemuda di lingkungan saya menghisap kretek. Baru setelah merantau ke Yogyakarta, saya mulai kecanduan untuk menghisap kretek, apalagi yang ada klembak menyan. Sungguh menggoda. Jauh dari itu, saya juga mengetahui kemudian, bahwa tembakau bukan hanya sebuah isapan, tapi pasar besar yang menghidupi ribuan, bahkan jutaan kepala.
Lebih jauh kemudian saya jadi tahu, mengapa iklan rokok seperti itu. Tidak ada unsur-unsur rokoknya, malahan hanya melalui rasa dan warna yang sarat dengan rokok tersebut hadir dalam visual. Tetapi, mereka mengiklankan itu dengan unik dan menarik.
Inilah poin penting yang tidak dimiliki oleh mereka yang di seberang: Mereka yang mengiklankan produk mereka namun menjatuhkan produk lain di waktu yang sama. Tembakau tidak hanya saja lintingan, namun juga pasar yang direbutkan dan menjadi sebuah medan perang. Sampai saya membaca buku yang berjudul “Perang Nikotin: Merenggut Denyut Ekonomi Kerakyatan”.
Dekolonialisasi terbalik
Dan ternyata, medan perang ini bukanlah imajinasi liar saya semata. Buku yang saya sebutkan sebelumnya, dan menjadi pemantik tulisan ini, secara gamblang memetakan arena pertempuran tersebut. Buku ini tidak bertele-tele. Langsung menunjuk hidung persoalan bahwa polemik tembakau yang terjadi bukanlah diskursus kesehatan yang organik, melainkan sebuah perang yang dirancang secara sadar dan sistematis.
Proses delegitimasi yang diuraikan dalam buku ini adalah sebuah operasi strategis yang berjalan secara sistematis. Ini dimulai dengan menetapkan industri tembakau nasional bukan sebagai aset, melainkan sebagai musuh bersama yang harus diperangi.
Senjata utamanya bukanlah konfrontasi fisik, melainkan wacana kesehatan dan moralitas yang digunakan untuk membingkai ulang isu yang tadinya kompleks menjadi masalah medis yang sederhana: kecanduan. Dengan narasi ini, nilai budaya dan kontribusi ekonomi tembakau sengaja dihilangkan, sehingga setiap upaya perlawanan terhadap regulasi ketat akan langsung dicap sebagai tindakan anti kesehatan.
Pelemahan struktural melalui sentimen publik dan kebijakan ini pada akhirnya bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah cara untuk menciptakan kekosongan pasar yang siap direbut oleh para pemain baru yang datang dengan jubah penyelamat.
Perang yang mereka maksud adalah manifestasi dari apa yang kita sebut sebagai imperialisme ekonomi dengan jubah dekolonialisasi yang terbalik. Jika dekolonialisasi adalah tentang merebut kembali kedaulatan, maka perang ini adalah tentang merampasnya kembali secara halus.
Buku ini menjadi bukti bahwa negara produsen tembakau seperti Indonesia, sebuah entitas Dunia Ketiga dalam peta kekuasaan global, sedang menjadi target dari sebuah operasi senyap. Operasi yang dijalankan oleh para pedagang obat modern yang, dengan restu lembaga lembaga multinasional, berusaha menguasai pasar nikotin dengan terlebih dahulu menghancurkan ekosistem ekonomi dan budaya yang telah ada berabad abad lamanya. Medan perang yang, terus terang saja, jauh lebih licik dari yang kita duga.
Marketing culas industri farmasi
Kita terlanjur nyaman dengan dongeng pengantar tidur yang disiarkan serentak di seluruh dunia: Di sudut merah ada Industri Tembakau, sang monster kapitalis bermodal asap yang rakus dan tak punya hati. Di sudut biru, berdiri para Ksatria Suci dari Industri Farmasi, lengkap dengan jubah putih, stetoskop berkilauan, dan didukung oleh malaikat-malaikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Misi mereka? Menyelamatkan umat manusia dari cengkeraman kecanduan. Satu dari sekian narasi yang begitu sempurna, dan tampak mulia. Namun ia begitu hitam-putih, sampai-sampai kita lupa untuk bertanya. Seperti yang dibongkar tanpa ampun oleh buku ini bahwa dongeng itu hanyalah sebuah kamuflase. Kampanye marketing paling culas dalam sejarah peradaban. Terdapat perang dagang yang dingin, perebutan kekuasaan atas komoditas bernama nikotin. Yang dilakukan dalam beberapa langkah dan bentuk.
Langkah pertama dalam perang modern adalah menguasai narasi. Mereka menciptakan monster yang begitu mengerikan sehingga tindakan apapun untuk membasminya terasa benar dan perlu. Dalam buku yang tengah kita bedah ini, secara detail memaparkan bagaimana monster Industri Tembakau ini diciptakan dan dipelihara.
Kita disuguhi cetak biru tentang bagaimana cara kerja perang wacana. Industri farmasi, dengan kemurahan hati yang mencurigakan, menyuntikkan dana hibah penelitian ke berbagai universitas dan lembaga nirlaba. Tentu saja, penelitian yang didanai adalah penelitian yang akan menemukan betapa jahatnya tembakau dan betapa adiktifnya nikotin setara heroin.
Para perokok tidak lagi dilihat sebagai konsumen dewasa yang membuat pilihan, tetapi sebagai pasien yang sakit, korban tak berdaya yang otaknya telah dibajak. Kakek saya yang menikmati kreteknya di beranda rumah? Menurut kitab suci kesehatan global ini, beliau bukan sedang menikmati hidup, beliau adalah penderita nicotine use disorder yang butuh intervensi medis.
Siasat demi siasat
Lebih lanjut apa yang terjadi adalah sebuah kekerasan epistemik (epistemic violence), di mana satu sistem pengetahuan (medis-Barat) dipaksakan secara universal, dan secara aktif menghapus serta mendelegitimasi sistem pengetahuan dan praktik budaya lainnya. Kretek, yang bagi jutaan orang di Indonesia adalah bagian dari ritual sosial, warisan budaya yang diracik dengan cengkeh dan rempah lokal, dimasukkan ke dalam keranjang sampah yang sama dengan rokok putih produksi korporasi multinasional.
Kearifan lokal, konteks sosial, dan rantai ekonomi yang menghidupi puluhan juta orang dari petani hingga pelinting, dianggap sebagai detail minor yang tidak penting di hadapan kebenaran ilmiah yang datang dari negeri entah berantah. Ini kemudian bentuk penjajahan yang paling subtil, penjajahan cara berpikir. Kita diajari untuk membenci produk budaya kita sendiri, dan pada saat yang sama, diajari untuk melihat produk modern dari Barat sebagai satu-satunya jalan keselamatan.
Tentu saja, narasi penyelamatan ini tidak gratis. Di balik kampanye cap jahat yang masif, ada motif ekonomi yang begitu telanjang. Haaa… inilah Aha! momen terbesar saat membaca buku ini. Perang ini sesungguhnya bukan untuk memusnahkan nikotin dari muka bumi. Itu bodoh dan tidak menguntungkan.
Perang ini adalah untuk merebut kendali atas jalur distribusi nikotin. Selama berabad-abad, nikotin dikonsumsi dalam bentuk yang murah, organik, dan tidak bisa dipatenkan. Ini adalah mimpi buruk bagi model bisnis farmasi yang hidup dari hak paten dan harga premium. Jadi, apa solusinya? Hancurkan sistem lama, dan bangun sistem baru yang mereka kuasai. Caranya?
Pertama, ubah nikotin dari produk agrikultur menjadi masalah medis. Kedua, tawarkan solusi medis yang kebetulan hanya mereka yang bisa memproduksinya. Voila! Permen karet nikotin, plester transdermal, pil varenicline, semua dikemas secara higienis, disetujui oleh lembaga-lembaga terhormat, dan dijual dengan harga yang membuat petani tembakau hanya bisa mengelus dada. Bermain dua kaki memang mengasyikkan, kamerad!
Ini adalah pola imperialisme ekonomi klasik yang diulang dalam skala global. Negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, yang merupakan produsen tembakau kelas dunia, diposisikan sebagai sumber masalah, sebagai pemasok racun terbelakang. Sementara itu, negara-negara industri maju, melalui korporasi farmasinya, memposisikan diri sebagai sumber solusi yang canggih dan beradab.
Mereka mungkin tidak lagi mengeruk rempah-rempah kita dengan kapal perang, tapi mereka kini mengeruk keuntungan dari molekul nikotin kita melalui resep dokter dan peraturan kesehatan global. Mereka menciptakan penyakitnya (kecanduan nikotin sebagai disorder), lalu menjual obatnya. Satu macam dari ribuan model bisnis yang sempurna. Pajak rokok yang dibuat melambung tinggi, dengan dalih menekan konsumsi, secara strategis juga berfungsi untuk membuat harga produk farmasi mereka yang mahal menjadi terasa lebih masuk akal.
Operasi senyap dan masif ini tentu tidak bisa dilakukan sendirian. Citra korporasi farmasi yang mata duitan perlu dipoles. Jaringannya rapi. Dana riset digelontorkan ke akademisi, donasi besar diberikan ke asosiasi-asosiasi kesehatan yang disegani, dan para pelobi ulung dikirim untuk berbisik di telinga para pembuat kebijakan.
Hasilnya? Asosiasi jantung yang kredibel tiba-tiba merekomendasikan produk X. Pemerintah, di bawah tekanan standar kesehatan global dari WHO (yang juga menerima kontribusi dari berbagai pihak yang berkepentingan), mengadopsi regulasi yang seolah-olah dirancang untuk menekan tembakau. Padahal secara efektif membuka jalan tol bagi produk-produk farmasi.
Kebijakan kesehatan di sebuah kabupaten di Jawa pada akhirnya ditentukan oleh hasil rapat dewan di New Jersey. Wajah baru neo-kolonialisme, satu sistem yang kedaulatan sebuah bangsa terkikis secara perlahan melalui standar, regulasi, dan praktik terbaik global yang sejatinya melayani kepentingan modal asing.
Perang nikotin bukan soal pro atau anti “rokok”
Membaca buku ini bukan lagi soal pro atau anti rokok. Buku ini memaksa kita untuk berhenti menjadi konsumen informasi yang naif. Ia membuktikan bahwa di balik setiap kampanye moral yang paling lantang sekalipun, sering kali tersembunyi agenda ekonomi yang paling banal. Ia tidak menyangkal dampak buruk merokok, tetapi ia menolak penyederhanaan masalah yang mengebiri konteks budaya, ekonomi, dan kedaulatan kita.
Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menerima begitu saja bahwa kretek kita adalah produk setan dan koyo dari luar negeri adalah juru selamat? Kita harus berhenti menelan mentah-mentah setiap standar global yang disodorkan.
Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia harus dirumuskan dari bawah, dengan mempertimbangkan realitas kita sendiri. Harus ada diferensiasi yang jelas antara kretek sebagai produk budaya-ekonomi nasional dengan rokok putih sebagai produk industri multinasional.
Kita butuh penelitian independen yang didanai negara, yang tidak hanya melihat tembakau dari lensa mikroskop patologi, tetapi juga dari kacamata sosiologi, antropologi, dan ekonomi-politik. Kita harus memproduksi pengetahuan kita sendiri untuk melawan hegemoni pengetahuan impor. Kita harus berpikir kritis. Alih-alih hanya menakut-nakuti dengan gambar paru-paru hitam, edukasi publik harus membongkar perang ekonomi di baliknya.
Biarkan masyarakat tahu bahwa saat mereka memilih antara kretek dan permen karet nikotin yang juga memiliki efek negatif, mereka tidak hanya membuat pilihan kesehatan, tetapi juga pilihan politik dan ekonomi.
Sepembacaan saya, buku ini tidak memberikan jawaban yang mudah. Ia justru meninggalkan kita dengan pertanyaan yang jauh lebih sulit dan penting. Setelah menyadari bahwa kita berada di tengah medan perang dagang global yang menyamar sebagai perang suci kesehatan, pertanyaan fundamentalnya bukan lagi bagaimana cara berhenti merokok?
Pertanyaannya adalah, “Bagaimana kita, sebagai sebuah bangsa, bisa merebut kembali hak untuk mendefinisikan masalah dan solusi kita sendiri, di tengah kepungan imperialisme berjubah putih yang begitu sistematis dan begitu meyakinkan ini?”
Kontributor Komunitas Kretek, Geri Septian
BACA JUGA: 3 Manfaat Nikotin bagi Tubuh Manusia
- Ibu Minah, Penjual Sayur Keliling Ketiban Rezeki Noplok: Menang Undian Mobil dari Pihak Djarum Selepas Mengikuti Jalan Santai HUT Temanggung 191 - 26 November 2025
- Rokok yang Dihisap Hadi (Fedi Nuril) dalam Film “Pangku” dan Jangan Ditiru! - 15 November 2025
- Soeharto: Bapak dari “Pencekik” Petani Cengkeh Bisa-bisanya Jadi Pahlawan Nasional - 10 November 2025